
Oleh F Pascaries
Pulau Buru itu berisi 13 ribu orang. Ada sekitar 23 unit. Masing-masing unit berisi 500 orang. Memang, mereka betul dipekerjakan layaknya budak. Demikian pengalaman di Pulau Buru yang dialami Oey Hay Djoen, salah seorang pegiat Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang sering diasosiasikan sebagai underbouw Partai Komunis Indonesia (PKI).
Oey Hay Djoen lahir di Malang, 18 April 1929. Di usia senjanya, sudah sekitar 30 buku berbahasa Inggris ia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira separuh dari yang aku terjemahkan adalah buku-bukunya Marx dan Engels. Kira-kira 16-18 buku.
Keterlibatan suami dari Jane Luyke (71 tahun) ini dengan PKI dimulai sekitar tahun 1955. Ia, yang baru saja tiba di Jakarta dari Semarang, diminta oleh PKI untuk bersedia dicalonkan sebagai anggota DPR dan Konstituante pada waktu itu. Padahal, pada waktu itu ia sama sekali belum tergabung sebagai anggota partai berlogo palu arit itu. Ia hanya aktivis Lekra.
Tahun 1957 ia terpilih menjadi anggota Sekretariat Pusat Partai. Di PKI tidak ada Ketua. Cuma ada Sekretaris Jenderal, dua orang Wasekjen, lalu anggota Sekretariat Pusat. Dari 11 orang, dengan Yumar Ayub sebagai Sekjen. Oey sendiri waktu itu memegang urusan rumah tangga dan bagian luar negeri.
Dari Salemba ke Pulau Buru
Soal peristiwa pembunuhan tahun 1965 ia mengaku memang tidak tahu. "Aku bengong saja. Pada tangal 1 Oktober baru dengar dari radio, tanya kanan kiri," jelasnya.
Pada 1 Oktober 1965 itu ia terlibat dalam Kongres KIAPMA (Konferensi Internsional Anti Pangkalan Militer Asing) yang ketua konferensinya pada waktu itu adalah Ny Utami Surya Darma. Oey termasuk dalam anggota utusan Indonesia, karena itu adalah forum internasional.
Kegiatan itu diadakan oleh OISRA (Organisasi Internasional Solidaritas Rakyat-rakyat Asia Afrika) yang pusatnya ada di Kairo, Mesir. Utusan Indonesia ini NASAKOM. Bersama, Nyoto (PKI), dan Edi Abdul Rahman (anggota parlemen yang juga Sekjennya Gerakan Perdamaian Dunia, yang kantornya di Jalan Raden Saleh), ia hadir di situ. "Jumlah anggota delegasinya kalau nggak salah 15 orang," katanya.
Konferensi yang diadakan di Bali Room Hotel Indonesia itu berjalan 4-5 hari. Tamu-tamu asing itu pulang tanggal 20 Oktober. Keesokannya, ia disergap oleh anggota Kodim di rumahnya (dulu di Rawamangun), untuk dijebloskan ke Rutan Salemba.
Waktu dibawa ke Kodim itu, ia sempat mau dikumpulkan dengan tahanan lainnya yang sudah ada di gudang belakang sana. Tapi ia menolak dan berkata, "Nggak bisa. Saya ini anggota parlemen, anda mesti minta ijin dulu untuk menangkap saya !" Karena itu, mereka tidak langsung membuang saya ke gudang belakang itu.
Hari berikutnya, ia dibawa dan dimasukkan ke Markas Polisi Militer Jalan Guntur Jakarta Selatan (tahu kan ?). Tengah malam ia dimasukkan ke Salemba lagi.
Esok harinya, setelah terang, baru ia dipindahkan ke blok R. Di situ ia bertemu Pramoedya Ananta Toer, Hasyim Rahman, dan banyak lagi yang ditangkap sebelumnya, sekitar tanggal 17 Oktober .
Sampai tahun 1969 ia ditahan di Salemba. Tahun 1979 bersama rombongan pertama ia dibuang ke Pulau Buru, setelah melewati sebulan di Nusakambangan. Kemudian, dengan kapal ia dibawa ke Pulau Buru.
Rombongan pertama ini memang berisi orang-orang penting. Seperti Pram, Redaktur harian Rakjat, Supit, anggota-anggota CC (Comite Central), dan pelajar-pelajar dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang pasti jumlah mereka 500 orang. "Nomor punggungku waktu itu 001 sedangkan Pram 007," ia mengenang.
Kedatangan mereka ke Pulau Buru, semula dirahasiakan, begitu juga seluruh perjalanan mereka. Baru belakangan diumumkan, bahwa mereka ditempatkan di Tefaat (tempat pemanfaatan) Buru.
Jadi, mereka (tentara) sudah berencana membuang para tapol itu dan memanfaatkan tapol menjadi budak. Jadi, seluruhnya memang keputusan tentara, yang memang berkuasa sejak adanya Kopkamtib itu.
"Kami diberitahu di sana, pokoknya kalian tidak akan pulang. Kalian hanya meninggalkan nama," ia menirukan tentara yang menjaga mereka di sana.
Mereka hidup dengan menanam padi, jagung, atau apa saja, bahkan menebang hutan, membuat minyak kayu putih dan sebagainya. "Itu semua dipakai (dieksploitasi) oleh tentara, " ia bercerita.
Ia menyarankan, kalau sempat, cari saja di surat-surat kabar di tahun 1970an. Di situ kita bisa temukan bahwa mendadak sontak Maluku mendadak jadi lumbung padi nasional.
Waktu pulau itu kami tinggalkan tahun 1979, sudah ribuan hewan yang sudah mereka ternak, ribuan hektar yang sudah menjadi sawah. Semua itu lalu dimanfaatkan oleh militer, dijadikan daerah trasmigrasi. Sampai sekarang, masih ada sejumlah eks tapol (ET) yang tinggal di sana, hidup berkeluarga.
Berbaur dengan Masyarakat
Para tahanan di Pulau Buru mengalami diskriminasi dengan embel-embel ET. Ia berkisah, mereka betul-betul diisolasi dari penduduk setempat. Sebelum ia dan rombongan pertama tiba di pulau itu, penduduk setempat sudah dijejali pikiran untuk tidak mendekati para tapol itu. Karena, tapol digambarkan sebagai pembunuh, pencuri, dan penjahat. "Jadi, penduduk pun juga takut terhadap kami," ia masih mengingat. Para tapol sangat berhati-hati, dan hanya bertemu dengan penduduk pada malam hari.
Para tapol itu memang dididik secara politik dan punya ideologi. Artinya, punya teori dan sebagainya, dan mereka terbiasa untuk kerja kolektif. "Dan kami tahu bahwa yang terpenting, jangan sampai terpisah dari rakyat," katanya.
Proses asimilisi yang pada awalnya memang tertutup, memakan waktu sekitar tiga tahun. Hingga akhirnya, Oey dan kawan-kawan bisa membuat suasana sedemikian rupa, sehingga bukan mereka (tapol) yang mengunjungi penduduk, tapi sebaliknya.
"Mereka pergi ke ladang-ladang kami, kami ajari mereka bagaimana bertani, bercocok tanam," katanya. Penduduk asli di sana yang masih primitif itu hanya hidup dari hasil mukul sagu, membuat tepung sagu. Seminggu, atau untuk beberapa lama, mereka menganggur tidak bekerja. Juga mencari ikan di rawa.
Setelah beberapa tahun, para warga sekitar bisa menjanjikan radio buat para tapol. Oey dan kawan-kawan datang setiap malam, jam-jam tertentu, untuk menyetel radio, tetap kucing-kucingan. Banyak anak-anak di sana yang sampai sekarang jika ditanya ingin jadi jadi apa, akan menjawab kompak, " Jadi tapol !". Karena, mereka melihat tapol sebagai orang yang serba bisa.
"Jadi, dengan cara-cara itulah. Cara-cara manusiawi yang biasa saja. Bukan dengan datang mereka, membuat mereka sadar polik. Halah....... omong kosong, " tutur Oey.
Pembutaan Sejarah
Ia bebas dari pembuangan pada tahun 1979. Ternyata, sejak ia ditangkap, rumahnya di daerah Rawamangun Jakarta Timur diduduki oleh satu kompi tentara. Rumah itu dijadikan tempat tahanan sekaligus tempat tinggal. Mereka mengusir istrinya, namun Ny Oey tetap bersikeras untuk tidak mau keluar dan tetap melawan.
Baru tahun 1979, ia mendapatkan kembali rumah itu. Salah satu petinggi ABRI pada waktu itu yang kenal dengan menantunya yang memungkinkan itu terjadi. Menantunya itu memberanikan diri dengan berkata "Pak, rumah mertua saya diduduki oleh tentara." Ternyata, petinggi militer itu langsung mengutus ajudannya untuk mengurus.
Ia menganggap, segala sesuatu terkait rekonsiliasi adalah omong kosong. Jangankan soal peristiwa yang sudah terjadi 40 tahun lebih, kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa orba pun banyak yang menguap begitu saja.
Oey berharap peristiwa 1965 jangan dianggap sebagai kejadian yang unik. Tapi, ia mengakui bahwa di tahun-tahun itu jumlah rakyat yang mati memang luar biasa besar. "Tapi, apa yang krusial itu juga unik? Tidak. Karena yang lain juga sama sebetulnya," tambah Oey.
Menurutnya, masalah terpenting bukan bagaimana mengampuni Soeharto. Cukup ada pengakuan bahwa memang telah terjadi kejahatan negara terhadap rakyatnya. Ia khawatir jika ini (peristiwa 1965) dianggap unik, akan terjadi pembutaan sejarah yang membodohi rakyat.
Singkatnya, menurut Oey, selama masih ada kekuasaan seperti ini, tidak akan terjadi pelurusan sejarah. Yang akan terjadi adalah supaya kita itu melupakan. Kita diajak untuk supaya seakan-akan melihat ke depan.
Peduliah pada Sejarah!
Buat orang muda, ia cuma bisa mengatakan, "Pedulilah pada sejarah, pada masyarakat, pada nasib bangsamu. Pokoknya, kejar ilmu pengetahuan. Dan, dalam menghadapi ilmu atau apa saja, pegang satu hal: bersikaplah kritikal !. Pokoknya, jangan percaya pada yang sudah 'dipatok-patok' itu. Sebab itu berarti habisnya ilmu, habisnya hidup ini. Sebab tidak ada sesuatu yang mutlak," ia menjelaskan dengan berapi-api.
Apalagi ini angkatan muda yang bebas, bisa mengenyam pendidikan, punya hubungan dengan luar negeri. "Jadi, mereka jadi orang paling peka dan tanggap soal-soal sosial," katanya. Jangan berharap dari pemerintah, harus dari kita sendiri. Bangun solidaritas, kenyataan bahwa semua kejadian itu adalah one and the same: konflik vertikal antara kekuasaan antara kekuasaan dengan sebagian rakyatnya. "Kalau begini, rakyat harus bersatu untuk menunjuk pelaku kejahatan yang satu itu. Kan sekarang nggak ada yang mengusahakan. Paling-paling oleh Tim Relawan Kemanusiaan (TRK) yang pernah mengadakan pertemuan-pertemuan yang mengundang orang-orang dari Talangsari, Aceh dan sebagainya. Tapi, belum jadi gerakan," ia prihatin.

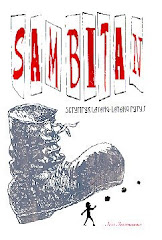



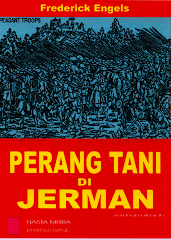


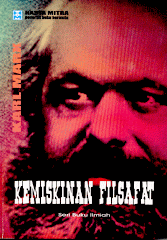


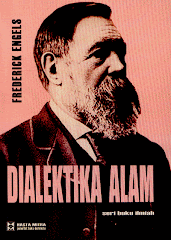
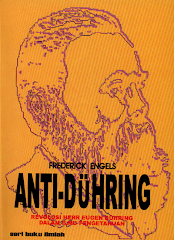
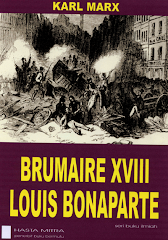

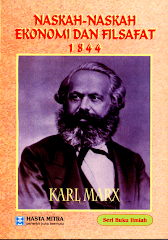
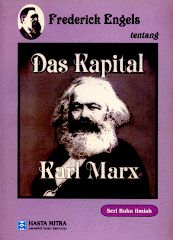
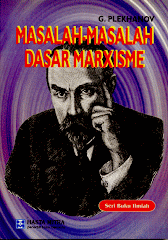
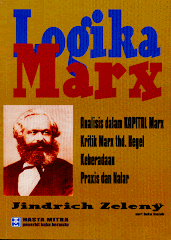
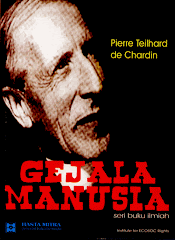


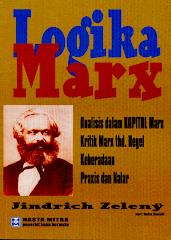

Tidak ada komentar:
Posting Komentar